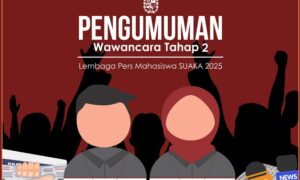Arian Pangestu*

Ilustrasi : Nurul Fajri
“Namaku Arunika, usia dua puluh tiga bulan Desember. Bersediakah Anda menjadi imamku, menuntunku ke luar dari kehidupan yang berlumur dosa ini, juga menjadi pelipur laraku dari derita yang tak bosan mengepung hidupku. Sungguhpun Anda akan menjadikanku istri yang ketiga atau keempat, dengan lapang dada sungguh aku akan menerimanya dengan sukacita,” tanyaku mula-mula pada lelaki berjenggot lebat itu.
Namun, lelaki itu pergi begitu saja setelah aku mengecupkan sesuatu yang tidak lazim dikecupkan perempuan jalang manapun, baik yang tempat mangkalnya kotor berteman nyamuk dan kecoa, hingga yang dipenuhi gemerlap warna-warni lampu cahaya. Sejatinya, lelaki itu adalah orang keenam yang menolak ajakanku untuk menikah.
“Tuhan yang manis kenapa nasibku pahit,” tanyaku dalam hati sambil mengadahkan wajah ke langit.
“Hei, Arunika, sudah jam tiga pagi kenapa belum satu pun menarik pelanggan,” tanya Bang Ben tukang ojek pribadiku.
Bila ada lelaki hidung belang yang akan memakai jasaku di hotel, Bang Ben yang akan mengantarku check-in dan check-out. Pekerjaannya akan sedikit lebih santai, hanya ngopi dan ngeroko jika ada tamu yang sudah diburu hawa nafsu. Sebab, Bang Ben tak perlu repot-repot mengantarku ke hotel karena bercinta di dalam mobil adalah alternatif pertolongan pertama.
“Entahlah Bang Ben, mungkin belum rezekinya,” sahutku pelan.
Dua-tiga batang rokok sudah menjadi abu dan Bang Ben masih menggerutu. Maklumlah rezeki dia ada pada tubuhku yang putih dan mulus ini. Bila ada tamu yang menjilati dadaku dan bersedia mengeluarkan uang 700 ribu dari dompetnya, maka Bang Ben akan mendapat bayaran dariku sebesar 150 ribu, itu belum dipotong uang keamanan 50 ribu setiap kali mangkal untuk jatah preman. Kalau semalam aku mendapatkan paling banyak enam pelanggan hidung belang dan paling sedikit setengahnya, maka hitunglah sendiri pendapatanku dan pendapatan Bang Ben tukang ojek pribadiku tentunya.
Sudah tiga bulan Desember profesi hina-dina lengkap dengan segala deritanya aku jalani dengan sabar. Kalau aku tak terpaksa melakukan pekerjaan hina di Kota Jakarta yang kejam untuk sebagian perempuan, mungkin sudah lama aku mati kelaparan.
Biarpun agama dan negara melarang, biarpun orang meludah dan menuduhnya sebagai sampah masyarakat, biarpun keluarga mengutuk, nyatanya pekerjaan ini menjamur di kota mana saja, terlebih Kota Metropolis. Inilah Jakarta, kota yang kejam dan hitam.
Siapa pun yang datang ke Kota Jakarta tanpa sanak-saudara, terlebih alpa ijazah, keterampilan dan pengetahuan, bila dia adalah perempuan, maka nasib yang paling baik menjadi pembantu di rumah orang. Sedangkan hal terburuknya adalah menjadi perempuan jalang macam diriku yang malang, yang tak punya siapa-siapa untuk dimintai pertolongan, kecuali seonggok tubuh ini yang sudah kuseret ke mana-mana.
Andai saja tiga bulan Desember yang lalu suamiku tidak menceraikanku, tentu malam ini aku tidak akan berada di tempat seperti ini. Tentu tiga bulan Desember yang kulalui akan diliputi bahagia bertabur bunga, tidak dicorang-moreng warna-warni dosa. Sebab, musibah itulah yang menghantarkan diriku di tepi bibir lautan dosa. Setidaknya aku sudah membunuh bayiku sendiri yang masih berusia hitungan bulan sebanyak tiga kali. Yang paling baru ialah hasil pekerjaanku sebagai perempuan jalang. Aku lupa lelaki hidung belang mana yang menaruh benih di rahimku.
Aku lupa malam apa saat membiarkan lelaki jahanam itu tak memasang alat kontrasepsi. Betapa malang anakku sayang, telah kurampas hidupnya ketika masih berwarna merah darah. Juga telah kuseka impiannya hidup di dunia, bahkan sebelum memanggilku mama.
Bayiku sayang bukan mama kejam. Mama hanya takut kau berjenis kelamin perempuan. Karena perempuan yang lemah selamanya harus bertakdir di bawah. Apalagi perempuan yang dianugerahi kecantikan. Ke manapun berjalan mata lelaki selalu memandang dengan tatapan tajam, seperti singa yang menatap domba. Kecantikan adalah cacat bagi seorang perempuan. Terlebih jika kau lahir tanpa ayah, hidupmu akan disengsarakan oleh penghidupan itu sendiri dan diinjak-injak oleh manusia yang disebut lelaki. Meskipun sejatinya semua perempuan sama, tetapi mata lelakilah yang memandangnya berbeda.
Bila kutengok lagi ke belakang, semua berawal saat suamiku pulang dari pengajian dan mendapati diriku sedang menerima tamu seorang lelaki, yang kebetulan tetangga baru. Aku dicaci maki tak karuan, segala nama bintang keluar dari mulutnya. Yang lebih menyakitkan, suamiku menuduhku dengan hal yang bukan-bukan. Tidak sedikit pun terlintas di benakku untuk mengkhianati suamiku, tidak sepercik pun terpikirkan untuk mengkhianati janji suci yang telah ku ikrarkan di atas kitab suci.
Sebagaimana filsafah haluan hidup seorang perempuan Jawa, yang bilamana kelak sudah menikah, maka akan diserahkan segenap hidupnya, akan diserahkan seluruh jiwa dan raganya pada sang suami. Sebab, yang dibutuhkan tiada lain hanyalah sebuah perlindungan atas dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, dan sebagai seorang ibu yang ringkih di bawah kekuasaan seorang lelaki yang disebut suami dan juga yang dilindungi oleh agama.
Namun, atas pertimbangan agama pula, tiba-tiba suamiku menceraikanku dengan kata-kata. Maklumlah, suamiku anak kyai terkemuka di kampungnya. Tentu alam raya pun tahu alasan purbasangka itu. Perasaanku hancur lebur bagai abu. Ternyata benar kata para pujangga, manisnya pernikahan paling lama hanya berusia tiga bulan, setelahnya akan terlihat perangai yang sebenarnya. Tepat tiga bulan usia pernikahanku, aku dibebas tugaskan dari tanggung jawab sebagai seorang istri.
Di Kota Jakarta inilah aku membanting kartu nasibku yang telah dituliskan oleh langit. Sebelum pada akhirnya kuputuskan menjadi perempuan jalang setelah beberapa kali dipermainkan oleh lelaki. Masih segar dalam ingatan, tiga bulan empat belas hari aku menjadi pelampiasan kelamin politisi…. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana kisah itu bermula. Terlalu rumit, begitu kompleks, atau barangkali pengetahuanku yang dangkal hingga aku tak tahu bahwa seks pun dipolitikkan.
Ringkasnya, tiga bulan tiga belas hari aku hidup di bawah sumpah agama, di bawah aturan nikah sirih. “Drama persetubuhan” pun berjalan lancar tanpa sepengetahuan istri si politisi… Namun, hingga usiaku di persembunyian apartemen politisi… genap berusia tiga bulan, tak ada tanda-tanda dia akan menjadi suamiku yang baik dan semestinya. Buktinya saat aku hamil, dia justru memaksaku untuk menggugurkan kandunganku, hanya karena takut karirnya sebagai politisi akan hancur lebur bila dipergoki oleh media. Setelah aku menuruti kemauannya, lagi-lagi dengan modal kata-kata aku diceraikannya dan ditendang keluar begitu saja.
Berselang tiga bulan kemudian, aku tinggal di rumah kos sambil bekerja sebagai buruh cuci dan masak. Lagi-lagi karena kecantikan, aku seperti keluar dari mulut buaya dan masuk ke mulut singa. Sebab, tidak lain ialah si pemilik kos yang berulang kali melecehkanku, hingga tragedi dalam hidup seorang perempuan mampir di hariku. Aku diperkosa setelah diberi obat tidur.
Minggu keenam belas telah berlalu. Kini aku menumpang tidur di rumah seorang perempuan setelah dikenalkan oleh tukang ojek saat aku terlunta-lunta di jalanan Ibu Kota. Perempuan muda, kaya, cantik, lincah, dan cemerlang. Dia begitu baik padaku, bahkan membantuku membunuh bayi dalam perutku.
Bila sesama perempuan sudah berkumpul tidak ada lagi yang namanya rahasia, justru sebaliknya yakni bertukar cerita.
Begitupun aku dengan perempuan itu, yang kini tepatnya sudah menjadi sahabatku, namanya Melati. Akhirnya, sebuah rahasia besar pun terbongkar dari mulutnya, ternyata dia seorang perempuan jalang. Katanya, kecantikan adalah modal bagi seorang perempuan untuk mendapatkan kekayaan dan kesenangan. Hal ini berbanding terbalik dengan keyakinanku, karena kecantikan adalah cacat dan kutukan bagi seorang perempuan.
Entah setan apa yang masuk ke dalam pikiranku hingga pada akhirnya aku tergoda juga oleh iming-iming uang bersayap kertas dan tidur di sangkar emas. Dua tahun kujalani profesi hina-dina sebagai perempuan jalang, dan aku lelah, setiap dalam kesepian dihantui rasa bersalah. Apakah selamanya hidupku harus karam di pusaran duka.
“Tuhan yang manis kenapa nasibku pahit,” gumamku dalam hati sambil mengadahkan wajah ke langit.
“Aruika kenapa menangis?” tanya Bang Ben.
“Aku lelah dengan semua ini Bang. Aku ingin hidup normal sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu. Aku merindukan hari-hari yang penuh cinta dan kasih sayang.”
“Kalau begitu aku yang salah sudah mengenalkanmu dengan Melati.”
Setelah diam sesaat Bang Ben melanjutkan, “Sungguh aku pun ingin hidup normal, mempunyai istri, menjadi imam dalam keluarga, hari-hari merayakan cinta, baik derita dan tawa akan dilaluinya selalu bersama. Namun, apalah daya, aku miskin segalanya, di perut dan otak, tak punyai keahlian dan alpa ijazah. Sudah tiga tahun pula pekerjaanku begini, mengantar perempuan-perempuan malam. Setidaknya sudah enam perempuan yang menggunakan jasaku sebagai tukang ojek antar-jemput, dari enam perempuan itu pula semuanya menolak saat kuajak untuk menikah dan hidup normal di bawah aturan agama dan negara.”
“Mari ke masjid azan shubuh sudah berkumandang. Tak ada yang benar-benar sepi, kecuali kita tidak bertuhan. Mari memohan ampunan,” tambahnya sambil menyelimuti tubuhku yang menggigil dengan jaketnya, kemudian membimbing tanganku.
“Bang Ben, namaku Arunika, usia dua puluh tiga bulan Desember, pekerjaanku sebagai perempuan jalang. Maukah Abang menjadi imamku, membimbingku ke arah jalan cahaya,” tanyaku yang membuat Bang Ben menghentikan langkah kakinya. Agak lama Bang Ben menatap mataku, dan kulihat matanya berair. Selanjutnya, tidak ada satu pun kata yang dikecupkan, kecuali satu ciuman mesra yang dialamatkan di keningku.
*Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Sastra semester akhir di Universitas Pamulang, Tangerang, Banten. Aktif pula di Sekolah Feminisme Jurnal Perempuan.