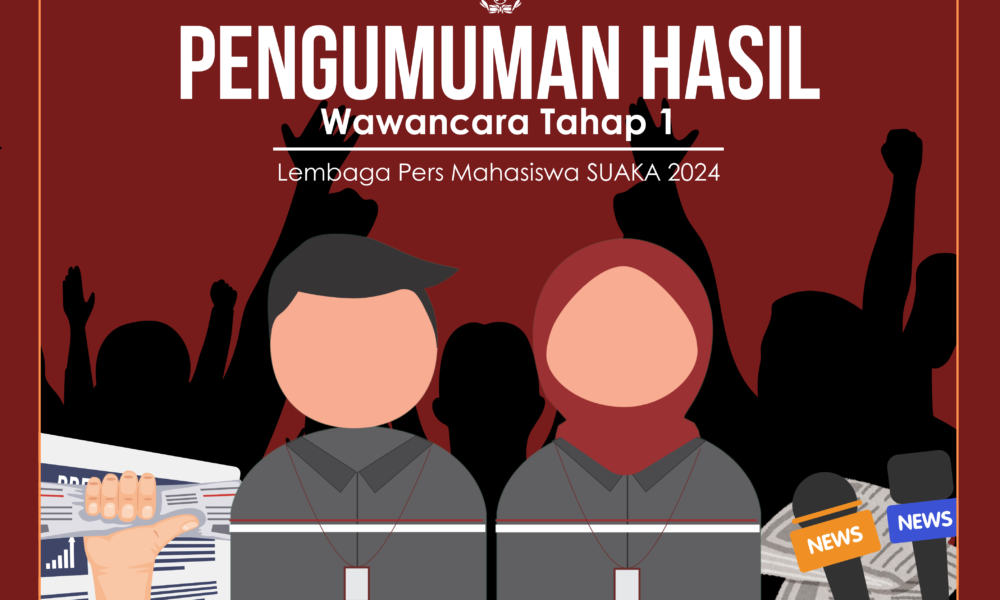ilustrasi oleh Nurul Fajri/SUAKA.
Oleh Triyo Handoko*
Setelah setahun diberikan hak milik oleh negara pada 4 Januari 1964, tanah itu digasak PT Perkebunan. Dibantu militer bersenjata, siapa yang berani melawan dan dituduh PKI.
Rumahnya dari Jalan Sragen-Balong masuk jalan dua tapak yang dibangun dari semen. Sekitar 500 meter dari halaman rumahnya adalah lahan yang secara hak milik belum dimilikinya. Namun, sudah dikelolanya secara sepihak sejak 2007. Namanya Sunarji, berbadan tegak, tinggi sekitar 168 cm. Berambut putih, berkumis putih, berjenggot lebat dan juga putih. Sudah sejak pecah reformasi mengorganisir petani Sambirejo untuk kembali mengambil hak atas tanah yang dirampas oleh negara sejak 1965.
Pada 16 Juli, dua minggu setelah lebaran 2017, sore itu selepas magrib ia pulang menghadiri hajatan pernikahan salah satu anak dari anggota Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS). Sebuah organisasi yang didirikanya untuk merebut hak milik tanah petani Sambirejo yang kini dikelola PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XI. Anggota FPKKS kini sekitar 700 orang yang tersebar di beberapa desa seperti desa Sukorejo, Jambeyan, Sambi, Sambirejo, dan Jetis.
Sambirejo sebagai sebuah kecamatan di Sragen berbatasan dengan Karanganyar di sisi selatan dan Ngawi di sisi Timur. Persis dengan wilayah kerja PTPN XI yaitu di Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Ngawi. Sebagai perusahaan berplat merah yang lahir sejak era Sukarno yang bertransformasi dari PT Perkebunan menjadi PT Perkebunan Negara (PTPN di era Suharto). Kini, PTPN tersebar ke seluruh Indonesia. Wilayah kerja PTPN kebanyakan menggunakan bekas lahan Perkebunan Belanda yang dinasionalisasi setelah merdeka.
Ada banyak jenis perkebunan yang dikelola PT Perkebunan Nusantara XI, seperti kopi, teh, janggung hingga karet. Di Sambirejo, PTPN XI mengelola perkebunan karet. Tanah seluas 400an hektar yang dikelola PTPN XI diawali dengan lumuran darah pembunuhan, pembuangan, dan api pembakaran perkampungan.
Sunarji, ingatnya, masih kelas empat Sekolah Rakyat ketika peristiwa itu terjadi. Tak jauh berbeda dengan petani lain. Orang tuanya dan paman-pamanya juga menjadi korban.
“Waktu itu di awal tahun 1966, saya dengan teman-teman sambil memanjat pohon melihat orang ditembak di pinggir liang tanah yang sudah disiapkan,” ceritanya.
Pelaku dari aksi semua kebiadaban itu adalah militer. “Di masa penjajahan Belanda tanah itu dijadikan perkebunan kopi dan tebu,” Sunarji mengawali cerita. Kemudian setelah Belanda bersama sekutu kalah di perang Pasifik, “Seperti sejarah pra kemerdekaan yang diajarkan sekolah, Jepang mengambil alih Indonesia termasuk tanah di Sambirejo ini,” lanjutnya dengan nada yang tenang tidak dibuat-buat.
Oleh Jepang, bekas perkebunan kopi dan tebu tersebut diubah menjadi perkebunan serat nanas. “Berbeda loh nanas dengan serat nanas itu, serat nanas itu untuk bahan sandang waktu itu. Sejenis serat pandan,” jelasnya dengan sedikit tertawa. Iklim politik yang tidak menentu, menurut Sunardi, karena perang dunia menjadikan perkebunan serat nanas mangkrak. Jepang disibukkan dengan urusan perang, lanjut pria yang suka membaca sejarah dan mengidolakan Pangeran Diponegoro dengan perang jawanya ini.
Setelah Jepang kalah dan Indonesia menyatakan merdeka, kemerdekaan itu juga dirasakan petani Sambirejo. “Kenapa? Karena petani Sambirejo bisa bebas bertani di tanah bekas perkebunan tersebut, yang juga tanah nenek moyangnya” ungkap Sunarji dengan antusias.
Semenjak Indonesia merdeka, cerita Sunarji, sisa-sisa bekas serat nanas tersebut dibersihkan kemudian dikelola oleh petani Sambirejo. Aneka ragam tanaman ditanam seperti palawija, jagung, kedelai, dan kacang. Tanaman untuk makanan pokok, seperti padi dan singkong hingga pepohonan yang bernilai jual tinggi, seperti pohon jati dan akasia. Semua itu jadi tumpuan hidup petani Sambirejo.
Sebelum peristiwa genosida 1965, menurut Sunarji, sudah ada penawaran pembelian tanah dari PT Perkebunan. “Petani, ya pada tidak mau, itu sumber penghidupan mereka jek,” cerita Sunarji dengan jengkel. Waktu itu PT Perkebunan bekerja sama dengan perangkat desa.
Genosida 1965 yang dilakukan militer lah yang menjadi kesempatan biadab PT Perkebunan. Membumihanguskan segala bangunan yang berdiri dan tanaman yang tumbuh adalah cara PT Perkebunan dibantu militer, kemudian membangun perkebunan karet. “Lewat Surat Keterangan (SK) Kepala Inspeksi Agraraia Daerah (KIND) tertanggal 4 Januari 1964 tanah-tanah itu legal secara hukum milik petani,” lanjut Sunarji. “Sungguh kalau mengenang kebiadaban itu kok ya negara tega-tegaya, gak habis pikir saya,” keluh Sunarji dengan menundukan kepala.
Pembantaian Anggota PKI Sambirejo
Sebelas orang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) Sambirejo dibunuh. Mereka adalah Sastro Tarmin dari desa Sukoharjo. Dari desa Sambi dua orang, Karjono dan Wignya Sumarta. Karto Wiryo dari desa Blimbing. Sastro Wiryo dari desa Sambirejo. Empat orang dari desa Kadipiro, Parmo Maji, Harso Tomo, Hadi Suroto, Hadi Siswoyo, dan Wiryo. Satu orang dari desa Jambeyan yaitu Sukirman yang sekaligus paman dari Sunarji. Isteri Sukirman yang kakak perempuan Sunarji, dibuang ke Pulau Buru selama tiga tahun.
“Jasa anggota PKI di Sambirejo dulu adalah mengorganisir petani agar tidak mau menyerahakan tanah garapan yang belum hak milik jatuh ke PT Perkebunan,” tutur Sunarji dengan khidmat. Tak hanya mengorganisir, anggota PKI juga mendorong agar tanah garapan petani Sambirejo segera diberikan hak milik secara hukum. “SK KINAD yang diperoleh itu kan upaya PKI,” tambah Sunarji sambil memantik api rokoknya.
Jika rumah Sunarji berada di timur Jalan Sragan-Balong, rumah Marni ada di barat Jalan Sragen-Balong. Rumah semi permanen yang menyampingi jalan dan menghadap ke utara tersebut tidak berubah sejak peristiwa genosida 1965. Pada 16 Juli 2017, aneka toples kue dan makanan ringan khas lebaran masih berjejer rapi di atas meja di ruang keluarga sekaligus ruang tamunya. Marni adalah saksi sekaligus korban genosida 1965.
Usia Marni 73 tahun, namun paras kecantikan masa mudanya masih berbinar. Beruban hanya dipangkal rambut. Giginya masih rapi dan melingkar cincin di jari manis dan tengah tangan kananya. Usianya baru 21 tahun ketika diseret ke penjara tanpa pengadilan hanya karena bersuami seorang anggota PKI. Suaminya, Hadi Suroto adalah bagian dari sebelas orang Sambirejo yang dibunuh militer. Prosesnya sama, tanpa melalui proses pengadilan.
Musim hujan 1965, hari itu adalah Kamis 9 Desember. Pagi itu hujan deras. Matahari menampakan diri ketika hari sudah siang. Di rumah hanya dengan anaknya yang baru berumur lima tahun, suaminya, Hadi Surato, sudah dibawa militer seminggu yang lalu. Tak ada kabar. Tak ada harapan. Begitu juga hari itu baginya.
Ditarik paksa dari rumah, dibawa mobil bukaan tertulis TNI AD. Marni sengaja tak akan melawan dengan menolak atau menangis. Pesan suaminya seperti itu. Hal itu menurut Marni untuk tidak mendapat tindak kekerasan dari militer. Namun sama saja, sesampai di kantor kecamatan, bersama para anggota dan simpatisan lain asal Sambirejo, diseret, dipukul, ditendang, dan dibentak-bentak tanpa satu hal pun yang Marni ketahui.
“Konflik 30 September 1965 itu kan konfliknya TNI sendiri, jendral dan perwira yang dibunuh oleh sama-sama militer juga,” jelas Marni. “Lantas apa salah kami di sini hingga diperlakukan seperti binatang,” keluh Marni. Hadi Suroto, adalah seorang tukang jahit biasa. Marni mengenang suaminya yang berbudi luhur dengan gagasan kerakyatan, kesetaraan dan persaudaraan yang bercita-cita keadilan dan kesejahteraan umum.
Marni akan ikut bergabung dengan rapat-rapat PKI atau Barisan Tani Indonesia (BTI), bersama suaminya jika tidak ada pekerjaan di rumah. Suaminya, kenang Marni, akan bergabung dengan kegiatan-kegiatan petani dalam BTI setelah mengerjakan pekerjaanya. “Pak Hadi itu orang yang teguh memperjuangkan tanah petani, walau dia bukan petani,” kata Marni denga mata yang berkaca-kaca.
Marni sejenak menengok foto hitam putih dan lusuh di dinding yang sama sejak 60 tahun itu. Foto itu foto Bung Karno. Tokoh yang diidolakan Hadi Suroto. “Kebetulan saja yang aktif dan giat membela rakyat di Sambirejo itu PKI, maka Pak Hadi bergabung dengan PKI,” lanjut Marni setelah meneguk teh. Tak ada yang salah bergabung dengan PKI. “Saya tak menyesal bergabung dengan Gerwani,” tegas Marni dengan yakin.
Selama diperiksa dengan tindakan kekerasan selama tiga hari. Marni selalu minum air parit pinggir sawah. Tak sudi baginya mengambil air minum yang sudah disediakan. Tak jelas bagaimana ia bisa bersalah dan ditahan tanpa tahu kapan kembali pulang. Anaknya, ia titipkan saudaranya. Selama dipenjara tak berhenti tindakan kekerasan menderanya. Dipekerjakan dari matahari bersinar sampai tenggelam, pernah ia lakoni. “Mengerjakan saluran irigasi dan saya bagian angkat batu,” terangnya.
Padahal jatah makanya sehari cuma sekali. “Bersama sekitar seratusan perempuan yang dipenjara tanpa sebab,” ingat Marni. Hari-hari dipenjaranya tanpa keterangan kapan dilepaskan. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Hingga hari itu adalah Jumat 30 Juli 1971, sebuah surat berkepala “LAKSUS KOPKAMTIB TEAM PEMERIKSA DAERAH DJAWA TENGAH” membawanya pulang ke rumah.
“Perih rasanya ditahan selama enam tahun dan terbukti tidak bersalah,” katanya. Dalam surat yang ditandatangani Mayor CPM Soemartono, membuktikan dirinya tidak bersalah. Duka hidupnya bukan berarti berkahir. Sesampainya di rumah, Marni bingung akan menjalani hidupnya seperti apa. Tak ada yang berani bergaul dengan dirinya. Streotip bekas tahanan politik itu terus dialaminya hingga hari ini. Walau sudah sedikit dibanding masa Orde Baru.
Keterbatasannya dilalui begitu saja. Apapun asal halal ia lakoni waktu itu. Berjualan makanan diteras rumah, ia lakoni. Sampai menerima pinangan seorang berpangkat di militer harus ia lakoni dengan ikhlas. Tak disebutkan siapa orang itu dan bekerja dalam bagian apa di militer. “Saya bertemu dengannya ya pas di penjara itu,” ujar Marni. Menjadi isteri kedua atau keberapa Marni tak tahu, “Yang penting bisa makan dulu,” kenangnya. Suami keduanya kini sudah tiada.
Bersama sebuah organisasi di Sragen yang fokus soal pembelaan korban genosida 1965, Marni terus berharap. Kini organisasi tersebut berisi 30an orang korban. Sunarji adalah salah satu pegiat di dalamnya. “Tahun 2015 itu anggotanya 150an, tapi seiring tahun berganti dan usia korban yang sudah sepuh makin hari berkurang,” tutur Sunarji datar.
Organisasi tersebut adalah ruang bersama memupuk harapan para korban. Setiap Sabtu pahing ada pertemuan semacam arisan. Sunarji belajar dari sana. Semangatnya terus dipupuk, walau sudah 19 tahun berjuang. Tak ada kata mundur baginya.
Status Hukum Tanah Sambirejo
Semenjak digasak PT. Perkebunan—yang kemudian menjadi PT. Perkebunan Negara XI—baru diketahui bahwa secara hukum tanah petani Sambirejo baru beralih hak milik pada tahun 1982. Ditetapkan di Jakarta tertanggaal 1 Juli 1982 oleh Daryono, Direktur Jendral Agraria Kementrian Dalam Negeri. Diketahui tanah yang disewagunakan oleh negara pada PT. Perkebunan Negara XI seluas 672,319 HA. Tanah seluas itu dimahar negara dengan nilai Rp840.000 yang harus lunas selama enam bulan. Selanjutnya uang sewa setiap tahun adalah Rp67.200.
Berbeda dengan pengakuan PTPN XI selama ini dengan luas lahan 400an Ha. Selanjutnya yang menambah geram Sunarji dan petani lain adalah status hukum selama 17 tahun setelah digasak PT. Perkebunan. “Siapa yang bisa menjelaskan status tanah selama itu? Apa penjelasan yang sesuai untuk tindakan itu? Selain pencurian, tidak ada!” ujar Sunarji dengan nada tinggi.
Tanah petani Sambirejo, bagi Sunarji, telah dicuri secara brutal selama 17 tahun oleh negara. Baru kemudian ada kejelasan Hak Guna Usaha dari 1982 sampai 2006. “Itu sama saja dengan pencurian yang dilegalkan,” kata Sunarji dengan percaya.
Setelah secara hukum diberikan hak miliknya kepada petani, mengapa kemudian diminta lagi dan dijadikan bagian dari aset negara melalui Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan, tanya Sunarji. Semua proses pengambilalihan status hak milik tanah itu pun tidak jelas. Tidak ada keterbukaan alih-alih mendapat ijin pemiliknya, yaitu petani Sambirejo.
“Negara dibawah Suharto kok jadi kaya gitu ya, jadi musuh rakyat,” ungkap kebingungan Sunarji. Berbeda dengan Negara dibawah Bung Karno. Sama seperti Hadi Suroto yang mengidolakan Bung Karno. Di teras rumah Sunarji terpapang poster Bung Karno seukuran 2×1 m. “Undang-undang (UU) yang sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) itu ya cuman UU Pokok Agaraia, yang lain ya sesuai dengan Orde Baru” celetus Sunarji.
Kegeraman Sunarji dirasakanya kembali. Negara melakukan kesalahan serupa. Walau tidak dalam cengkraman Suharto, perjuangan untuk mengambil tanah milik petani Sambirejo sejak tahun 1998, menjadikan tanah tersebut sebagai sengketa. Permen Agraria 9/1999 menyebutkan bahwa tanah sengketa tidak bisa diproses penerbitan perizinanya.
Diketahui pada 14 Januari 2013 bersama Konsosrsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan LSM Elsam, petani Sambirejo mendatangi Kementrian BUMN. Kenyataan pahit itu adalah mengetahui PTPN mendapat izin HGU kembali. Pahitnya lagi, menurut Sunarji, izin terbsebut dikeluarkan sejak 2010.
“Ada beberapa petani Sambirejo masih memegang SK KINAD, mereka berhasil mengamankan bukti kepemilikan tanah dari milter,” lanjut Sunarji. Suharto adalah contoh petani Sambirejo tersebut. Sehingga jelas proses tersebut cacat adminstrasi dan berarti membuktikan adanya sengketa tanah. “Tapi kenapa Negara sebegitunya melukai kami, mereka sendiri yang membikin perundang-undangan dan juga mereka sendiri yang melanggarnya,” keluh Sunarji.
Kini Sunarji berharap besar pada program reforma agraraia Jokowi-JK. Bersama KPA, Sunarji dan pengurus FPKKS kerap diundang untuk menanggapi program tersebut. Misalnya 8-9 Juni 2017, Sunarji menjadi narausmber Lokakarya yang diadakan Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Agraria, dengan tema “Percepatan Reforma Agraria”
Sunarji dalam lokakarya tersebut berpesan bahwa pejuang reforma agararia harus dilibatkan dalam teknis redistribusi tanah objek agraria. “Bahkan saya waktu itu berpesan jangan sampai proses reforma agraria melahirkan konflik agraria baru karena ketidakadilan proses redistribusi,” ingat Sunarji.
Usep Setiawan, Tenaga Ahli bidang Kajian dan Pengelolaan isu Ekologi, Sosial, dan Budaya KSP yang juga Majelis Pakar KPA 2016-2020 memang menyayangkan berbagai konflik agraria yang melibatkan PTPN. Usep yang dihubungi via telpon mengatakan, “Ada banyak konflik agraria dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi bahkan Jawa yang melibatkan PT Perkebunan.”
Menurut Usep, proses penyelesaiannya sulit jika berurusan dengan perusahaan plat merah tersebut. Usep menjelaskan politik-hukumnya belum mendukung kemenangan petani yang berkonflik. “Proses pelepasan tanah harus melewati Kementrian BUMN dan Keuangan karena bagian dari aset negara,” terang Usep.
Sehingga perlu ada trobosan politik-hukum yang orientasinya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perjuangan petani Sambirejo kini menunggu hasil. Proses adminstrasi untuk menjadikan tanah mereka sebagai bagian dari tanah objek agraria telah diurus oleh KPA Jawa Tengah.
Sementara proses menunggu dan kemenangan itu di depan mata, aksi-aksi sepihak pengelolaan tanah sudah dimulai sejak 2007 hingga kini. Kesejahteraan petani Sambirejo kian hari kian meningkat, dengan bertani jagung di bekas tanah yang ditanami pohon karet. “Aksi penanaman tersebut sudah kami lakukan pada 300-an Ha dan ini adalah bukti bahwa tanah tersebut memang sudah ditelantarkan PTPN,” tutup Sunarji Senin malam itu.
*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan juara 2 lomba menulis feature dalam lomba kejurnalistikan yang diadakan oleh LPM Suaka dalam rangkaian Milad ke 32 Tahun