Oleh Anisa Dewi Anggriaeni*
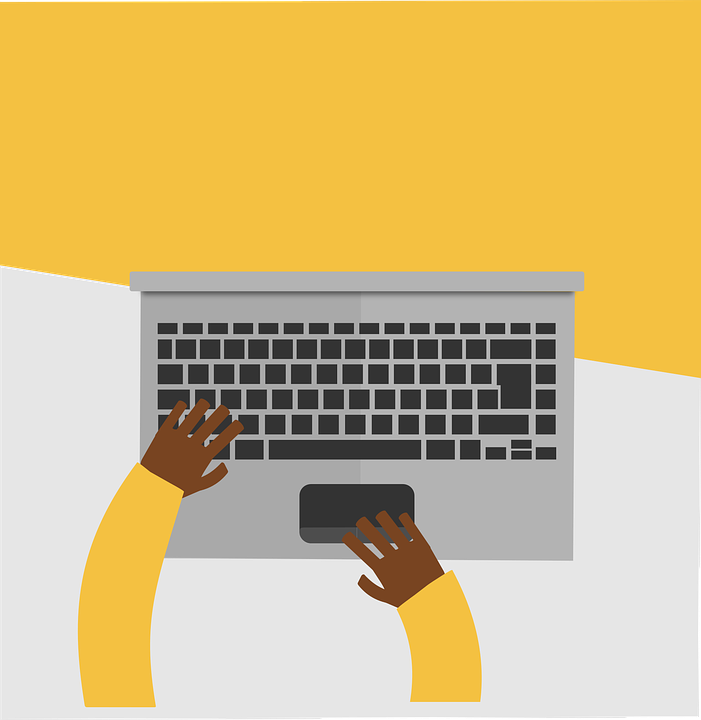
Dok. net.
“Hal yang dilakukan oleh kekerasan adalah menciptakan kebencian di antara umat manusia dan menciptakan ketakutan. Tidak akan ada perdamaian atau keselarasan lahir di tengah-tengah umat manusia di dunia kecuali anti kekerasan dipraktikkan, karena anti kekerasan adalah cinta kasih dan cinta kasih itu mengorbankan cinta kasih pada manusia” ungkap Eknath Easwaran dalam bukunya Nonviolent Solider of Islam.
Perdamaian tidak lepas dari kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya mesti berkontribusi mewujudkan perdamaian. Perempuan tidak perlu lagi terjebak oleh konstruk sosial yang mendomestifikasi dirinya. Terjun ke ruang-ruang publik bahwa perempuan juga punya peran penting dalam meredam konflik yang tengah berkecamuk ini.
Mundur sejenak ke bulan Mei kemarin, tentu publik tidak asing dengan peristiwa pengeboman markas Brimob dimana terdapat dua mahasiswi yang membaiat diri pada ISIS dan membantu penyerangan dengan memberi makan pada Napi teroris. Selang tak berapa lama bom juga meledak di tiga Gereja Surabaya. Pelakunya satu keluarga dengan pembagian tugasnya masing-masing. Seorang ibu dengan membawa dua anaknya. Perempuan tidak lagi menjadi pasif bahkan dalam kasus ini, mereka menjadi kombatan. Doktrinisasi yang dilakukan oleh golongan ekstrimis kepada pelaku menjadi PR besar bagi perempuan, utamanya untuk menularkan niai-nilai perdamaian.
Sialnya narasi-narasi semacam itu yang terus disajikan kepada publik ‘perempaun berani’ yang bernada negatif. Sehingga stigma yang muncul perempuan dianggap liar, mudah terperdaya, dan sebaris kelemahan yang lain. Sedikit sekali perempuan berprestasi yang terekspos. Prestasi dalam hal ini tentu saja bukan sekedar akademik tapi segi pendidikan dalam artian luas, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sebetulnya perempun sudah berkiprah di setiap lini, hanya saja masih ‘lirih’ dominasi patriarki masih sangat kentara.
Melihat contoh berita yang dirilis BBC.com tertanggal 13 Mei 2018 dengan judul Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri ‘perempuan yang membawa dua anak’. Berita tersebut membubuhkan kata perempuan yang menjadikan bias. Mendeskripkan bahwa perempuan masih menjadi objek, eksploitasi media dalam pemberitaan.
Bila mengetik di mesin pencari dengan kata ‘perempuan’ maka sederet narasi negatif yang muncul disana. Semakin membuat perempuan harus lebih lantang lagi menyuarakan keadilan dan kesetaraan beserta hak-haknya. Untuk menyuarakan kembali suara yang lirih itu salah satu jalan yang perlu ditempuh dengan terjun di ranah literasi. Membaca, diskusi, menulis dan edukasi adalah seperangkat senjata yang mampu mengubah paradigma masyarakat luas. Melalui tangan-tangan pembawa pesan damai, informasi dapat tersebar luas apalagi ditunjang dengan era digital, seperti sekarang.
Semakin sering berlatih mempruduksi narasi, semakin mengetahui bagian mana saja yang bakal dipangkas. Ketika kepenulisan mengedepankan angle, sebab angle adalah sudut pandang yang beragam. Sayangnya seringkali manusia kehilangan kesanggupan menuliskanya padahal jelas sudah nampak dalam kehidupan sehari-hari.
Semacam lonceng dalam kepala untuk otokritik demi kehidupan yang mencerdaskan bangsa. Nalar kritispun akan terpelihara dengan terus mengasah melalui kata demi kata dalam tulisan. Menulis merupakan media dalam mengawal realita sosial. Melalui kata-kata atau kalimat dengan nada mengkritisi, menghadapi fenomena sosial, kita turut menyumbang pemahaman bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja kompleksitas yang mencuat sebagai inspirasi untuk menuangkan gagasan.
Media Perlu Jurnalisme Damai
Setelah memproduksi narasi alias menuangkanya dalam tulisan tentu saja yang dibutuhkan selanjutnya adalah media. Media menjadi alat edukasi dalam mengakses informasi, ia memiliki wewenang untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Secara tidak langsung media turut menyumbang pola pikir kepada masyarakat. Sayangnya, jarang media secara spesifik mengangkat isu keberagaman yang cover all sides.
Media mainstream atau media arus utama menyuguhkan informasi terkait konflik SARA misalnya dengan mencari benang merah. Bukan menawarkan solusi atau menyajikan dengan tidak menghakimi pihak manapun. Indepensi dari jurnalisnyapun dipertanyakan. Sebagai seorang jurnalis ketika di lapangan tentu segala macam latar belakang harus dilepaskan.
Upaya membendung pemberitaan yang tidak berimbang apalagi bila merugikan, perempuan harus mampu membuat tandingan. Meluruskan hal yang sekiranya menyimpang dengan menulis opini di media misalnya. Atau para jurnalis perempuan yang getol mengawal isu keberagaman tanpa mencari titik konflik dan berhenti disana tetapi menawarkan solusi agar kejadian yang sudah-sudah tak terulang lagi.
Jurnalis punya andil besar dalam meredam sengketa SARA, bukan malah membiaskan berita yang berdampak pada munculnya emosi massal. Tidak diberinya ruang dan kesempatan pada minoritas untuk menggemakan suaranya atau justru memposisikan mayoritas sebagai pihak yang tak bersalah.
Kalau ditilik lebih lanjut kekacauan dan konflik yang melingkupi masyarakat meletakan media menjadi medan terpenting, selain sebagai pilar demokrasi keempat. Itu yang perlu dicatat, penggunaan istilah information worldwar bukan hal yang mendidik publik. Fokus terpenting media adalah sejauh mana ia menentukan keberhasilan dan kesuksesan untuk mewujudkan perdamaian.
Jurnalis perempuan harus mampu menuntun medianya mewujudkan perdamaian bukan turut serta membombardir masyarakat dengan berita yang kontroversial atau sensasional. Apalah arti clickbait demi terciptanya kedamaian yang hakiki. Rasa damai yang menancap dalam hati.
Johan Galtung sudah memformulasikan jurnalisme damai agar perdamaian segera lahir dan kekerasan diminimalisir. Ia membedah beberapa prinsip untuk mempelajari jurnalisme damai. Salah satu yang disampaikan adalah suatu dikotomi berupa bagan yang dapat dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda. Antara praktik jurnalistik yang diorientasikan pada perdamaian atau praktik jurnalitik yang fokus pada konflik, secara sadar atau tidak sadar diarahkan pada pertengkaran.
Jean Baudlriard dalam The Gulf War Did Not Take Place dalam perang tidak semua citraan yang ditampilkan oleh media merupakan representasi dari realitas kekejaman perang yang sesungguhnya. Citra kekejaman itu dapat diciptakan simulasinya di sebuah studio televisi atau di sebuah tempat (Pseudo place ) melalui teknologi yang canggih.
Jurnalisme damai lebih beorientasi pada perdamaian atas konflik yang tengah terjadi ,dalam hal ini pihak yang berkonflik bukan hanya dua, sebut saja A dan B. Tetapi lebih jamak bahkan di posisi A sendiri ada A1, A2 atau A3. Itu yang menggambarkan perbedaan jurnalisme damai mengamati hal-hal yang lebih kompleks secara komprehensif. Juga berorientasi pada kebenaran, melihat akar konflik, struktur serta peta secara rinci.
Sedang, Jurnalisme perang atau istilah familiarnya war journalism meliput suatu bentrok dengan semangatisme, melihat inti dari permasalahan hanya dari satu sisi. Analoginya ketika melaporkan sebuah pertandingan olahraga yang selalu ada dua pihak, loser and winner mereka bertikai kemudian menanti pemenang. Orientasinyapun pada hal yang bersifat propaganda, tidak turut serta meredam konflik.
Kenyataan yang ada media justru acuh trehadap penayangan yang berbau perdamaian, media kerap menampilkan sudut pandang konflik. Itulah yang memunculkan bad news is good news. Seharusnya media memberi edukasi berupa tayangan atau pemberitaan yang mengarah pada toleransi agar mampu meminimalisir konflik-konflik yang belakangan sering muncul menggegerkan publik. Tentunya sumbangish mewujudkan perdamaian, minimal damai sudah sejak dalam pikiran.
Herry Nurdi dalam buku Living Islam pikiran seperti parasut penerjun. Dia bekerja dengan sempurna ketika sang penerjun atau pemilik pikiran itu sendiri mau membukanya. Kian besar pikiran manusia terbuka kian besar pula manfaat dan sudut pandang yang bisa diambil olehnya. Kian terbuka pikiran manusia kian besar pula sumbangan dan kontribusi yang akan diberikanya.
*Penulis adalah Kepala Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LPM Suaka, mahasiswi Sastra Inggris UIN Sunan Gunng Djati Bandung
























