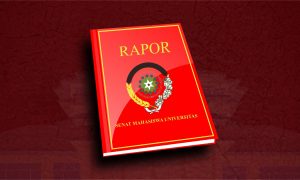Dok. Net
Oleh Ridwan Alawi
Mei 2015 silam presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kebebasan kepada para pewarta asing untuk melakukan peliputan ke tanah Papua. Penyataan itu disampaikan Jokowi pada Panen Raya Kampung Wapeko Kecamatan Hurik, Kabupaten Merauke, Minggu (10/5).
Kabar itu pun disambut gembira. Pelbagai kalangan mengekspresikan kegembiraan mereka, terutama wartawan asing. Mulai dari cuitan di media sosial hingga langsung booking tiket penerbangan menuju Papua untuk mencari berita.
Sekilas hal itu seperti harapan. Namun sayang, Jokowi hanya menjadi pemberi harapan palsu. Atau pernyataan Jokowi yang mencabut syarat ketat pers asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua itu cuma sebagai sikap reaktif atau spontanitas semata. Jelas bukan mempertimbangkan substantif.
Yakni respon cepat dari desakan dunia internasional atas kasus ditangkapnya dua jurnalis Perancis, karena menyalahi izin paspor. Dan tanpa kita sadari, pemerintah selama ini kerap kali membuat kebijakan reaktif, termasuk dengan menangani pemberitaan asing tentang Papua.
Saya rasa wajar sekali bila Indonesia menjadi tuan rumah perayaan world press freedom day (WPFD) 2017 yang berlangsung di Jakarta (1-4/5/2017). Satu alasan, karena polemik kebebasan pers di Indonesia memburuk. Ini lah yang mengganjal indeks kebebasan pers Indonesia.
Memang peringkat Indonesia pada Indeks Kebebasan Pers Sedunia tahun ini naik enam peringkat ke 124. Dalam indeks yang dirilis pada Rabu, 26 April 2017 oleh Reporters Without Borders. Posisinya tepat di bawah Qatar dan di atas Angola. Tahun lalu Indonesia berada di posisi 130, tepat dibawah Algeria.
Tapi pada awal 2017, ada dua orang netizen di Algeria dibuikan. Peringkat Algeria kemudian turun menjadi peringkat 134 pada indeks tahun itu. Artinya meski Indonesia mengalami peningkatan, kenaikan peringkat Indonesia juga dikarenakan negara-negara lain mengalami situasi yang lebih buruk.
“Secara keseluruhan, situsai memburuk di hampir dua pertiga negara (62.2 persen) dari 180 negara,” rilis yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders.
Memang kebanyakan wilayah di Indonesia kondisinya stabil, namun bila kita lihat dua provinsi paling timur: Papua dan Papua Barat, itu akan membuat kita mengelus dada. Tanah cendrawasih ini menghadapi masalah serius: pembatasan pada wartawan asing, kekerasan dan diskriminasi terhadap wartawan dan penyuapan adalah lazin di sana.
Jurnalis Tabloid Jubi di Papua Yance Wenda, dianiaya aparat kepolisian ketika meliput demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura, Senin (1/5/2017). Dia mengalami luka di pelipis, bibir, mata, kepala dan punggung.
Sehari sebelumnya tiga jurnalis di Papua mengalami ancaman pembunuhan saat meliput sidang sengketa Pilkada di Pengadilan Negeri Jayawijaya, Papua. Sebulan lalu, dua jurnalis Prancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dideportasi dari Timika saat melakukan kerja jurnalistik. Ini masih remah dari masalah besar yang ada.
Cacatan merah di rapor Indonesia lainnya pun masih ada. Setiap tahun terus meningkat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sepanjang Mei 2016 hingga April 2017 terjadi 76 kasus kekerasan, dibanding 2015 sebanyak 44 kasus. Sementara Januari-April 2017 sebanyak 24 kasus.
Kekerasan terhadap jurnalis terus terulang karena lemahnya penegakan hukum. Polisi gagal mengungkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami jurnalis. Kekerasan dikhawatirkan akan meningkat tahun depan karena bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak.
Kekerasan yang dialami jurnalis meliputi intimidasi, perampasan alat kerja, pemukulan dan menghalangi kerja jurnalistik. Pelaku kekerasan antara lain organisasi masyarakat, polisi, aparat militer dan aparatur pemerintah.
Pun masyarakat Indonesia masih ingat dengan delapan kasus kematian jurnalis yang belum terungkap. Terjadi impunitas, atau pembiaran oleh aparat penegak hukum. Mereka adalah Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersa Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).
Kasus ini harus diusut tuntas menggunakan Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers. Pada Pasal 18 pelaku diancam hukuman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.
Kekerasan juga dialami Pers Mahasiswa. Data Pengurus Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) sepanjang 2013-2016 terjadi 64 kasus kekerasan yang dialami Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Sebagian besar berupa intimidasi dan pembredelan. Jawa Timur menjadi provinsi yang terbanyak LPM mengalami kekerasan, disusul Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menghadapi situasi ini kita mesti menuntut aparat penegak hukum serius menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih media massa sebagai sumber informasi dan melek media dengan segala hukumnya.
Pihak media pun seyogyanya menjaga independensi dan menolak intervensi ruang redaksi dari pengaruh siapapun. Serta meneguhkan diri menjadi jurnalis yang berpedoman UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam melaksanakan kerja jurnalistik.
Semoga Indonesia menjadi negeri yang demokratis dengan tegaknya pilar keempat demokrasi: pers. Mesti terlewat, selamat merayakan hari kebebasan pers internasional.
*Penulis merupakan Koordinator Suaka Institue 2016-2017