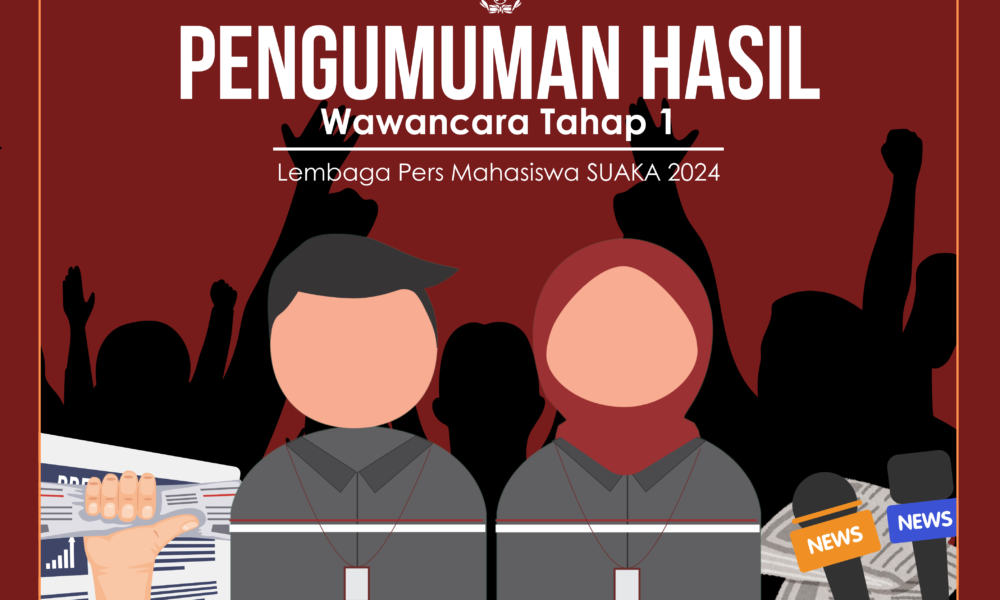Dok. Net
Oleh Riswan Taufik Masdiana
Saat ini negeri kita tengah ramai-ramainya membicarakan politik-agama, politik yang dipinang agama, serta agama yang dipersunting oleh politik. Sebuah diskursus yang menjalar dari mulut para pejabat di gedung-gedung parlemen -hingga ke obrolan pedagang kaki lima di pinggir pasar- ditemani oleh kepak sayap lalat yang tuli akan percakapan manusia. Seperti kematian Hegel yang berujung pada perpecahan antara mazhab Hegelian Kanan dan Kiri, pasca kemeriahan Pilgub Ibu Kota serta aksi massa yang berjilid-jilid itu, kini warga muslim semakin terpecah belah menjadi banyak kubu. Alhasil, topik perihal politik, agama, intoleransi rasanya mirip bubur ayam; digandrungi oleh manusia usia belia hingga dewasa akhir.
Perbincangan seputar intoleransi (terhadap yang berbeda atau satu agama) sudah menjadi diskursus panjang yang mewarnai ruang pemberitaan di negeri ini. Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang kasus intoleransi atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), pada tahun 2014 tercatat ada 76 kasus dan 87 kasus pada 2015. Sementara sepanjang 2016 mengalami peningkatan yakni tercatat ada 97 kasus. Dalam acara penyampaian laporan tahunan tentang kondisi KBB yang digelar di Ruang Pengaduan Komnas HAM pada Senin, (9/1/17) tersebut, Staf Komnas HAM, Jayadi Damanik mengatakan berdasarkan data yang diterima Komnas HAM pada 2016, Jawa Barat adalah daerah dengan jumlah aduan tertinggi, disusul oleh DKI Jakarta pada urutan kedua.
Teknologi telah merubah cara interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, salah satunya ialah aksi intoleransi yang terjadi di sosial media. Jika dahulu aksi intoleransi dilakukan dengan cara tradisional yakni bertatap muka (face to face), maka dengan adanya medium non-fisik tersebut kini para pelaku justru lebih liar dalam menjalankan aksinya. Menjamurnya postingan-postingan audiovisual (tulisan, gambar, suara, dan video) yang mendiskriminasi atribut, pemikiran, atau pun amalan yang berbeda seakan menjadi barometer kuantitas aksi intoleransi terhadap sesama muslim di dunia maya (dengan akun anonim atau akun pribadi).
Karenanya, di era yang serba digital ini kita semestinya berkaca pada zaman nabi di mana inklusivitas dan toleransi beragama sangat dijunjung tinggi saat itu, yang kemudian ditransformasikan pada zaman sahabat, terutama pada masa Sahabat Umar bin Khattab ketika penaklukan Palestina. Sejarah mencatat bahwa Umar masuk Gereja dan memberikan pidato yang melarang tentaranya untuk merusak bangunan-bangunan suci dan simbol peradaban yang ada di Palestina. Jangankan merusak, mencemooh saja dilarang dalam Islam.
Kearab-araban dan Sarkasme
Telah menjadi sebuah panorama sosial yang jamak kita temui jika seorang perempuan dengan pakaian tertutup lengkap dengan niqab (cadar), lelaki bercelana di atas mata kaki (cingkrang) dengan janggut yang dipanjangkan, serta kaum muda yang dicap ‘kearab-araban’ akan menjadi santapan liar cemoohan dalam sebuah postingan di sosial media. Diamini oleh pengguna lain, maka seketika kolom komentar menjadi kubangan sarkasme. Mirisnya, jika ditelusuri lebih lanjut, akun yang memposting atau pun akun-akun yang ikut meramaikan kolom komentar tersebut, konten-konten di beranda mereka justru banyak berbicara perihal toleransi dan ke-bhinneka-an.
Bukankah setiap orang berhak mengekspresikan dirinya termasuk dalam mengutarakan pandangan hidup dan keagamaan yang dianutnya? Bukankah tubuh mereka adalah otoritas mereka? Bukankah mereka dan kita sama-sama punya landasan teologiko-politis yang kuat? Apakah tak lelah mencemooh ekspresi diri mereka-sementara kita sendiri tetap “keukeuh” beribadah dengan atribut kita; batik, blangkon, dan sarung? Bukankah kita adalah pejuang demokrasi dan kebebasan berekspresi? Kita tentu tidak ingin mengulang kembali terpasungnya kebebasan berekspresi di ruang publik intelektual.
Saya rasa, jika negara-negara Eropa telah tercebur ke dalam Islamophobia, maka negeri ini justru tercebur ke dalam Arabphobia. Mirip dengan Amerika yang terbius oleh propaganda anti-Islam pasca tragedi 9/11, lalu menempatkan Islam sebagai personifikasi setan dunia yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Maka situasi historis-politis serta maraknya postingan aksi radikalisme-ekstrimisme yang mana sering menempatkan perempuan bercadar, para pria celana cingkrang dengan janggut panjang, serta mereka yang ‘kearab-araban’ sebagai sosok yang identik dengan fasis, ektrimis, radikal seakan menjadi suplemen bagi propaganda yang tengah mewabah agar kita menjadi semakin takut dan benci terhadap sesuatu yang berbau Arab.
Jika alasannya untuk menangkal fasisme, ekstrimisme, radikalisme, rasa-rasanya kita telah melakukan generalisir yang begitu kejam terhadap mereka. Ibarat Islam bukanlah Arab dan Arab bukanlah Islam, maka yang bercadar, celana cingkrang, dan mereka yang ‘kearab-araban’ pun tidak dapat begitu saja kita labeli sebagai fasis-ektrimis-radikalis. Perihal perempuan bercadar yang menjadi pro-kontra serta ada yang memandangnya sebagai korban tradisi patriarkhi yang kuat mengakar dalam Islam-sehingga mereka (yang mempunyai pandangan bahwa bercadar adalah budaya patriarkhi yang kemudian ditransmisikan menjadi tradisi Islam) menjadi kontra terhadap perempuan bercadar, maka sebagai pejuang kebebasan berekspresi-sudah semestinya kita menghargai pandangan hidup serta teologiko-politis yang dianut oleh mereka (bercadar, celana cingkrang, dan ‘kearab-araban’). Kembali lagi, bercadar, celana cingkrang, berjanggut, serta ‘kearab-araban’ adalah ekspresi diri.
Kemudian, jika atribut kearab-araban tak disukai karena tidak sesuai dengan budaya nusantara, apakah sejarah mencatat bahwa budaya yang kita sebut sebagai “budaya nusantara” ini adalah benar-benar budaya asli Indonesia yang tercipta sendiri dan mandiri, ataukah justru terinfluence oleh negara-negara luar juga, India misalnya. Bukankah Indonesia dan Arab juga terlibat akulturasi budaya seperti halnya India-Indonesia. Lantas mengapa peci dan sarung berbeda nasib dengan niqab dan celana cingkrang?
Padahal, kita justru adem ayem dan biasa saja dengan manusia-manusia negeri ini yang mengimitasi manusia-manusia dari negeri lain; Eropa misalnya. Rasanya amat jarang bahkan tidak akan ada yang akan protes atau menjadi korban cemoohan ketika seorang pemuda muslim mengenakan kemeja serta celana jeans dan mengucap kata “sorry” ketika melakukan kesalahan atau kata “thank you” saat berterima kasih. Sementara pemuda yang mengucap kata “Afwan, syukron, ana-antum” justru akan diperlakukan sebaliknya.
Dislike Berbeda dengan Disagree
Seperti kata almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; toleransi itu harus disebarkan di internal dan di antara agama-agama itu sendiri. Tidak pernah merasa paling benar (truth claim). Karena toleransi yang sesungguhnya tidak sekadar hidup berdampingan secara damai dalam suasana saling menghormati dan menghargai, tetapi juga adanya kesadaran dan kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran luhur dari agama atau keyakinan berbeda. Dengan toleransi itulah, suasana damai dan dinamis bisa dijaga dan kemuliaan ajaran agama menampakkan wujudnya. Lebih dari itu, toleransi harus diwujudkan dalam kesediaan untuk saling belajar, memberi dan menerima (take and give) di antara umat beragama.
Toleransi yang diajarkan dan dipraktikkan Gus Dur tidak sekadar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama dan peradaban lain itu sendiri. Gus Dur menyatakan bahwa ia akan menerima dan menyampaikan kebenaran yang datang dari manapun, apakah itu datang dari Injil, Bhagawad Gita, atau yang lain (Abdurrahman Wahid, “Intelektual di Tengah Eksklusivisme,” Prisma, No. 3, Maret 1991).
Dalam bukunya yang berjudul The Childern of Adam: an Islamic Perspective on Pluralism, Fathi Osman menegaskan makna pluralisme dan toleransi (h. 2-3), toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konfik. Pluralisme, di satu sisi, mensyaratkan ukuran-ukuran kelembagaan dan legal yang melindungi dan mengesahkan kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara manusia sebagai pribadi atau kelompok, baik ukuran-ukuran itu bersifat bawaan atau pun perolehan.
Toleransi menuntut suatu pendekatan yang serius dalam memahami pihak lain dan kerja sama yang membangun untuk kebaikan semua. Semua manusia seharusnya menikmati hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang sama, dan seharusnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama sebagai warga negara dan warga dunia. Setiap kelompok semestinya memiliki hak untuk berhimpun dan berkembang, memelihara identitas dan kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam negara dan dunia internasional.
Akan menjadi hal yang mengerikan jika intoleransi terus disebar dan dipupuk di hadapan massa. Jika memang tidak setuju dengan pemikiran atau sikap mereka maka utarakan dengan kritik atau gagasan disertai dengan alasan yang berkualitas, bukan lantas mencemooh. Kritik sangatlah berbeda dengan cemoohan, bobot kritik dinilai dari kualitas argumentasinya. Jika kritik timbul dari ketidaksetujuan, maka cemoohan muncul dari ketidaksenangan semata. Dissagree merupakan miliknya kritik, dislike miliknya cemoohan. Kritik yang baik tentunya haruslah objektif, lugas, dan rasional. Pun disertai dengan tata krama dalam penyampaiannya.
Apalagi kita selaku mahasiswa yang secara sosio-kultural dan sosio-politik dicap kaum intelektual yang memiliki semangat garis depan berkat tritunggal intelek, dedikasi, etik dalam pergaulan. Sebagaimana dalam piramida sosial, kaum intelektual adalah mereka yang mempunyai kelengkapan dan berperan di struktur-atas berkat prestasi-reputasi diri yang unggul dan berkerakyatan demi terciptanya toleransi, demokrasi dan tegaknya hak asasi manusia secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara, kaum intelektual ialah mereka yang harus benar-benar memahami dan mengamalkan substansi dari toleransi itu sendiri. Karena toleransi itu ibarat Marxisme; ia bukanlah suatu dogma melainkan suatu pedoman untuk bertindak.
Sumber:
www.suakaonline.com
www.komnasham.go.id
www.indoprogress.com
Mohamed Fathi Osman The Childern of Adam: an Islamic Perspective on Pluralism, Washington DC; Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, 1996.
Intelektual di Tengah Eksklusivisme, Prisma, No. 3, Maret 1991
*Penulis merupakan Anggota Bidang PSDM LPM SUAKA UIN Bandung